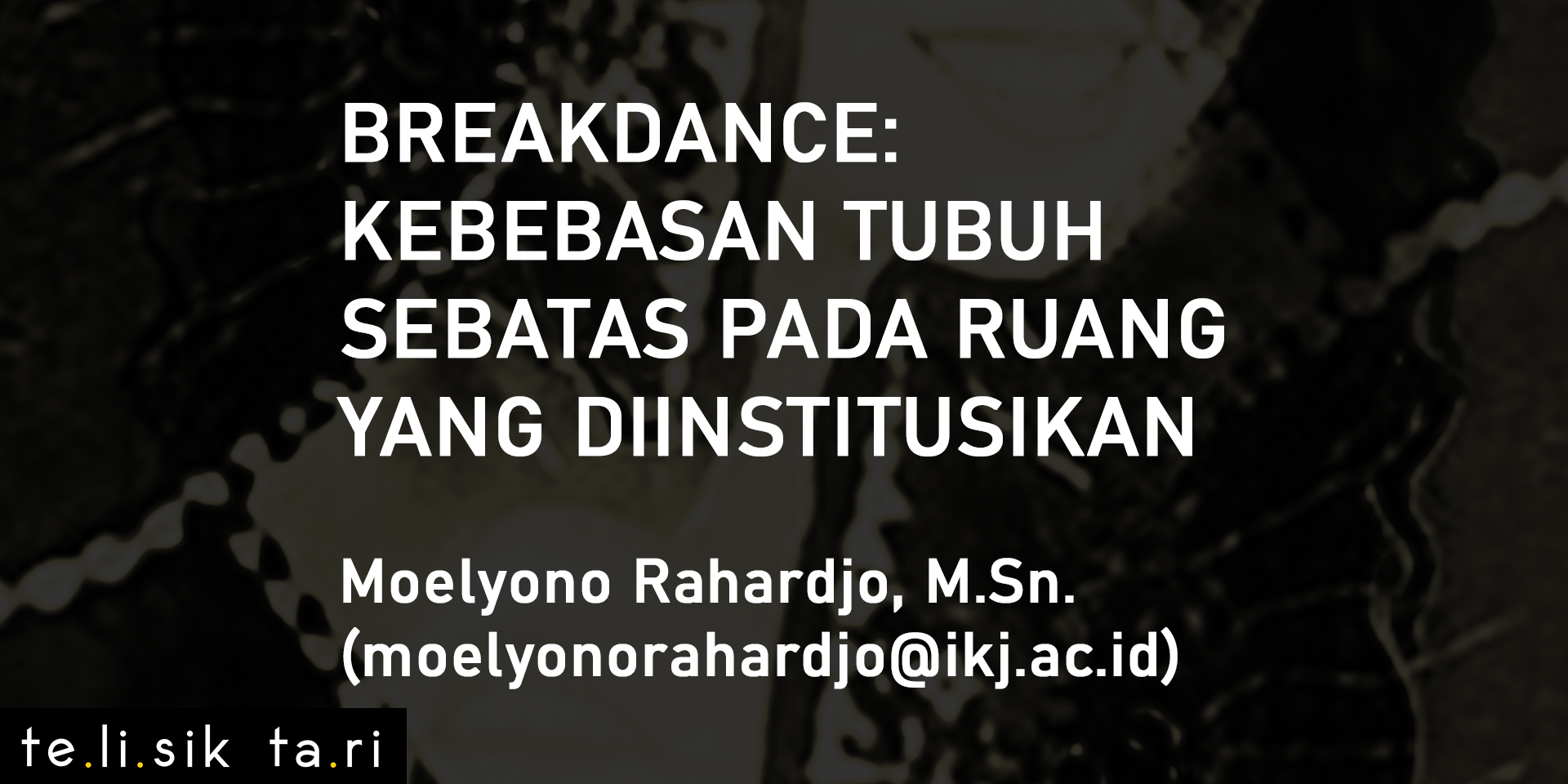Perbantahan seru mengenai tren breakdance terjadi di media surat kabar di Indonesia pada masanya. Kegiatan breakdance yang dilakukan oleh kaum muda di tempat umum dianggap mengganggu ketertiban umum, tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan kebudayaan Indonesia, termasuk perihal nilai-nilai agama, serta dikhawatirkan terpengaruh miras, narkoba, seks bebas, maupun prostitusi. Mereka yang mendukung, menganggap breakdance sebagai kegiatan olah raga belaka, yang bentuknya dianggap mirip dengan tari tradisional seperti Tari Reog, Tari Cakil, atau Tari Bali. Di antara opini dari yang mendukung dan yang menggugat pun muncul opini perihal perlunya pelatihan dan arahan, serta usaha untuk menginstitusikan kegiatan informal kaum muda, yang sifatnya berkelompok ini, agar ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang negatif yang dikhawatirkan terjadi. Walaupun sebenarnya hampir tidak ada larangan resmi dari pemerintah daerah, pelaku breakdance sering kali menjadi korban razia. Mereka dibubarkan dan bahkan ditangkap oleh pihak berwajib untuk kemudian dilepas kembali sesudah pelaku dijemput oleh orang tuanya. Di sisi lain, kegiatan breakdance yang bersifat institusional, seperti pada kegiatan luar sekolah, lomba di sekolah, lomba di diskotik, maupun di area-area yang dianggap pantas untuk berkegiatan breakdance, tidak dipermasalahkan oleh pihak yang berwajib, kecuali jika terjadi kekacauan atau perihal lain yang dikhawatirkan.
Dari Bagian Dokumentasi Dewan Kesenian Jakarta, pada kolom harian Sinar Harapan, Selasa, 29 Januari 1985, “Breakdance Sebagai Prestasi”, ditulis oleh Ariel Heryanto, nampak adanya kekhawatiran yang berujung pada penghakiman yang dilakukan oleh kaum yang lebih tua, atas apa yang tidak/belum mereka pahami dari kegiatan breakdance oleh kaum muda tersebut, menjadi satu tema besar yang mengurung perbantahan tersebut. Hal ini terbaca dari penggunaan analogi maupun terminologi yang justru membahas apa yang berada di luar dari dan tidak ada hubungannya dengan breakdance itu sendiri. Sebagai contoh, pemahaman atas gerakan breakdance yang merupakan akar dari solusi kreatif atas perkelahian antar geng di Amerika, dibandingkan dengan tari tradisi yang mungkin justru tampak jauh dari apa yang dipahami oleh kaum muda. Penggunaan terminologi breakdance menjadi “tari kejang” (lainnya: dansa kesurupan, tari robot, tari rusak, tari irama pecah) pun memperlihatkan bagaimana reduksi dan bias yang dilakukan oleh kaum yang lebih tua (istilah yang digunakan dalam tulisan Heryanto) sebagai usaha untuk menekan, merendahkan, dan membatalkan kegiatan ini akibat kekhawatiran mereka sendiri yang semestinya kurang memiliki landasan logis yang kuat. Sepertinya, usaha untuk menginstitusikan kegiatan sporadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kaum muda di kota hingga sudut kampung ini dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada kaum yang lebih tua. Heryanto pun mengategorikan tidak hanya perihal kaum muda dan kaum yang lebih tua, melainkan juga perihal kaum gedongan dan jelata. Pemisahan antara kaum gedongan dan jelata ini pun disanggah sendiri oleh Heryanto. Mengingat bagaimana breakdance selain mengusung soal gerakan, juga membawa unsur-unsur musik, piranti pemutar musik (mini compo dan walkman), fesyen, gaya hidup, video referensi yang kesemuanya membutuhkan modal sosial maupun modal ekonomi untuk memperolehnya.
Dari breakdance kita dapat melihat bagaimana solusi atas perlawanan antar geng berubah menjadi gaya hidup, lalu diadopsi oleh kaum muda di Indonesia menjadi gaya hidup, yang kemudian menimbulkan fenomena perbantahan atas ruang terbuka kota sebagai panggung, mengutip Heryanto yang membandingkan moda tontonan yang cuma butuh karton boks rongsokan dan gedung pertunjukan seharga 14,3 juta rupiah. Perbantahan di ruang media ini pun menjadikan kaum pedagang pernak-pernik pelengkap gaya hidup, penyelenggara acara pentas, pemilik tempat pertunjukan, dan media menangguk untung, sedangkan breakdance meredup tak lama setelahnya. Sepertinya usaha menginstitusikan kegiatan breakdance bukan hanya sekadar keberadaan pihak penanggung jawab, seketika kegiatan tersebut menjadi kegiatan komersial yang terlokalisasi, perbantahan pun lambat laun senyap. Kebebasan ekspresi tubuh kaum muda pada ruang kota disuarakan oleh media, diperbantahkan oleh kaum yang lebih tua (pejabat, tokoh agama, budayawan dan intelektual) untuk diinstitusikan, namun setelah muncul tata cara dan arahan, kebebasan ekspresi itu pun ditinggalkan kaum muda untuk beralih pada tren gaya hidup yang lain, laiknya tren rock and roll, disko dan tren rambut gondrong yang berangsur-angsur ditinggalkan sebelumnya.
Dari berbagai liputan perbantahan di media, terlihat dominasi ada pada opini kaum yang lebih tua ketimbang pada opini kaum muda pelaku breakdance itu sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa interaksi tubuh dan ruang kekinian saat itu hanya sebebas pada hal yang diamini oleh kelompok dominan, yaitu kaum yang lebih tua. Kompetisi antarkelompok yang menjadi akar breakdance, untuk mendapatkan pengakuan dari sesama pelaku, pun ikut berubah menjadi kompetisi yang dijurikan oleh kaum yang lebih tua. Keterlibatan kaum yang lebih tua tersebut menjadikan sifat institusional dari breakdance muncul sekaligus meredakan perbantahan yang terjadi.