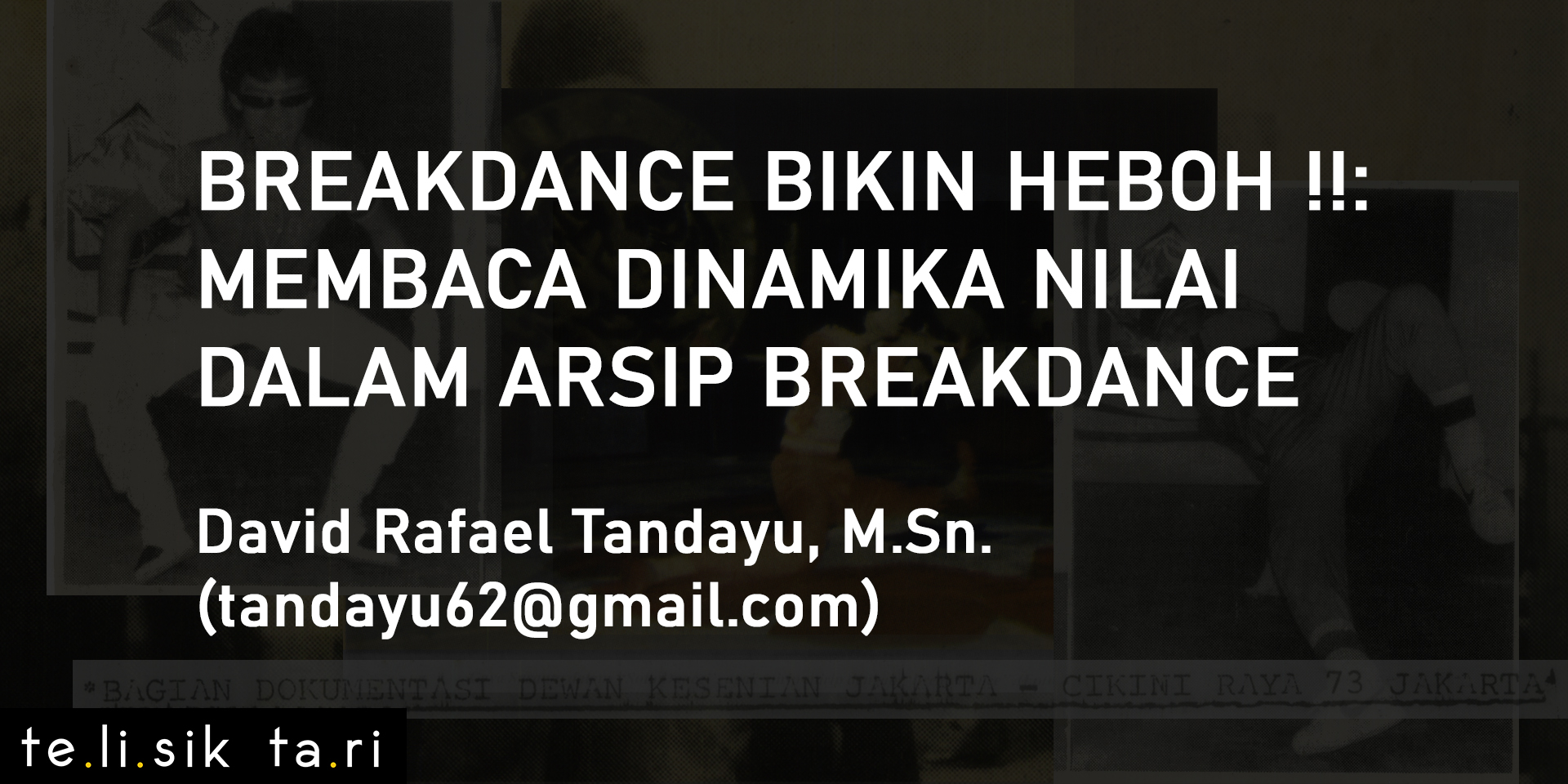Mencermati breakdance berdasarkan arsip Komite Tari-Dewan Kesenian Jakarta, secara mendasar perihal yang mengemuka adalah spasial dan temporal; bahwa di sisi timur Amerika, yaitu di South Bronx-New York, pada era ‘70 tumbuh gerakan -budaya- hip hop.
Dengan pengertian bahwa breakdance adalah bagian dari hip hop, saat breakdance sampai di Indonesia sekitar satu dekade kemudian, hip hop sendiri justru tidak banyak disebut; sementara arsip breakdance yang dicermati menunjukkan kedatangan breakdance di Indonesia -umum- disambut dengan pandangan negatif. Apakah hal tersebut mengindikasikan bahwa breakdance tidak ditangkap beserta muatan budayanya sehingga pemahaman tentang breakdance menjadi tidak utuh?
Wajar bila breakdance dianggap asing di luar konteks geografisnya. Bila New York adalah penanda (spasial) keurbanan di Amerika–seperti Jakarta di Indonesia, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta pada era ’80-an terkait breakdance adalah fenomena khas urban berdasarkan adanya kolektivitas nilai. Khusus bagi kaum muda Jakarta, breakdance sebagai hal asing dimaknai sebagai hal baru–yang ternyata menarik untuk dikenali sampai dicoba dilakukan. Breakdance pun mulai terlihat di ruang-ruang kota sampai dilombakan; terlihat baik karena tari ini merupakan bukti kemampuan fisik sesuai kelompok usia muda, merupakan kegiatan mengisi waktu sampai dilakukan atas nama ekspresi pencarian jati diri.


Bahwa breakdance kemudian dipandang negatif dapat diamati sebagai suatu dinamika yang menyertai realitas berkolektivitas nilai. Dalam arsip, breakdance diberitakan dengan diterjemahkan menjadi ‘tarian gila’, mengandung gerakan erotis yang dipertontonkan di ruang publik.
Fenomena breakdance lantas menjadi bahan diskusi dengan kaum berusia lanjut turut bicara. Bagi kaum berusia lanjut, kaum muda adalah generasi penerus bangsa; sementara disadari bahwa keadaan terus berubah yang memunculkan tantangan zaman. Perkembangan teknologi adalah hal yang disebut membawa pengaruh luar dan bagaimana menyikapi pengaruh luar adalah salah satu tantangan. Muatan diskusi pun meluas; dari mulai dipertanyakannya perihal pendahulu dan pembaharu sampai bicara tentang tradisi (baca: masa lalu) dan (ter)kini.
Dinamika turut diwarnai dengan penyikapan yang ekstrem terhadap breakdance–dengan disebut sebagai penyakit dan gerakannya yang seperti orang kesetanan. Muncul kekhawatiran yang dialamatkan pada kemungkinan celaka fisik sampai dihubungkan dengan pornografi -karena pakaian breakdance yang dikatakan terbuka- sehingga dihubungkan pula dengan aspek moral bangsa; termasuk perihal kekosongan budaya pada kaum muda–sehingga diisi oleh hal-hal dari luar yang dibawa oleh teknologi. Sampai di sini, terlihat bahwa diskusi tentang breakdance menjauh dari membahas dance itu sendiri. Alih-alih tentang aspek formalnya, breakdance dibenturkan dengan perihal lain di luar estetikanya -semendasar- sebagai manifestasi seni berbasis gerak.



Kembali pada mempertanyakan apakah breakdance tidak ditangkap secara utuh dengan segala muatan budayanya, setidaknya secara lokal pembahasan perihal budaya tumbuh dari dinamika pro dan kontra. Keadaan beradu dan/atau berpadu dapat dipandang lumrah ketika perihal tradisi berdampingan dengan modernitas; dalam hal breakdance, modernitas yang dimaksud mengacu pada keurbanan–berdasarkan asal breakdance dan kemudian ruang yang didatangi (baca: menerima). Demikian konflik dapat dipandang sebagai potensi.
Keurbanan di Indonesia sendiri dapat ditelusuri kesejarahannya–yang (kembali) terkait dengan perihal kolektivitas nilai; bahwa untuk mendapat pengertian tentang dinamika, membahas perihal spasial dan temporal perlu digerakkan. Problematisasi breakdance pada era ’80-an bukanlah laku baru; bahwa mempermasalahkan hal asing sudah sedari sebelumnya–mengacu pada upaya membangun identitas bangsa -sebelum membangun perekonomian-. Demikian tumpang-tindih menjadi realitas.
Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa breakdance sendiri adalah sepersekian manifestasi budaya luar bila dibandingkan dengan transformasi keurbanan -lokal- yang prosesnya meliputi konstruksi nilai, membedakan antara pusat dengan pinggir, menata wajah kota sampai membuka peluang bagi pemodal luar. Sementara munculnya beragam infrastruktur bak kemajuan (baca: menjadi modern), upaya berbasis jati diri berskala bangsa mengiringi.
Sebagai renungan, realitas tumpang-tindih dapat berujung pada mempertanyakan hal ini: dalam keurbanan, apakah dinamika seperti yang disampaikan di atas relevan? Atau bila terlalu dini untuk merenung dan/atau mempertanyakan, terlebih mengingat adanya arsip breakdance selain yang ditunjukkan dalam artikel ini, maka dipandang baik untuk melanjutkan penelusuran arsip.
Disadari bahwa akan terbangun suatu kompleksitas dengan melanjutkan membaca arsip; secara organik baik karena muatan arsip dan untuk memetik manfaat dari problematisasi perihal budaya. Kembali pada memandang konflik sebagai potensi, problematisasi dipandang dapat menjadi jalan bagi membangun kebaruan–sejauh mana yang diperlukan; termasuk mencermati dalam arsip, bilakah problematisasi breakdance kembali, dikembalikan, atau setidaknya mendekat pada breakdance dan tari itu sendiri.
Referensi:
Braembussche, Antoon Van den. 2009. Thinking Art: An Introduction to Philosophy of Art. Springer.
Johnson, Richard et al. 2004. The Practice of Cultural Studies. SAGE Publications Ltd, London.
Miksic, John N. 1989. Jakarta: A History. By Susan Abeyasekere dalam Journal of Southeast Asian Studies / Volume 20 / Issue 01. Senn, Krishna & Hill, David T. 2000/2007. Media, Culture, and Politics in Indonesia. Oxford University Press/PT Equinox Publishing Indonesia, Jakarta.
Shackford-Bradley, Julie. 2003. Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia by Abidin Kusno dalam Indonesia, No. 75 (Apr., 2003). Southeast Asia Program Publications, Cornell University.